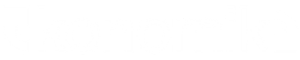Saya masih mengingat betul masa ketika menulis terasa sebebas bernapas. Apa saja yang lewat di kepala, langsung saya tuangkan ke dalam tulisan, entah curhatan, ide-ide aneh, bahkan kalimat-kalimat random menggelitik yang tidak berarti. Namun, begitu memasuki bangku kuliah, kebebasan itu seakan menghilang. Bahkan untuk menulis esai ini pun saya sempat ragu. Bukan karena tidak ada ide, tapi karena takut tidak sesuai sistematika yang diminta. Saya jadi lebih peka pada detail-detail kecil seperti, ‘menulis itu tidak boleh dan harus begini dan begitu’ yang dulunya tidak pernah saya pikirkan. Pikir saya dulu, “menulis ya menulis aja”, tapi sekarang berbeda. Saya cenderung lebih berpikir dua kali sebelum mulai menuangkan gagasan saya ke dalam medium. Dari sinilah saya berpikir, apakah sistematika menulis ini benar-benar mendorong nalar kritis dan alur berpikir saya, atau justru sebaliknya?
Pembatasan Ruang Argumen Berkedok ‘Sistematika Menulis’ Menurut KBBI, menulis diartikan sebagai “melahirkan pikiran atau perasaan melalui tulisan”. Artinya, menulis bukan sekadar merangkai kata, tetapi juga sebuah proses menuangkan ide, gagasan, bahkan perasaan ke dalam medium tulisan. Dari definisi ini, terlihat bahwa esensi menulis sebenarnya adalah kebebasan berekspresi. Namun, di dunia akademik, kebebasan itu sering kali dibingkai oleh aturan-aturan tertentu yang disebut sistematika. Kita seolah dicekoki narasi bahwa menulis itu harus begini dan begitu. Dalam konteks karya ilmiah, misalnya, katanya tulisan harus bebas dari subjektivitas: jangan menggunakan kata saya, kami, bahkan mereka. Keterangan waktu seperti “hari ini” atau “akhir-akhir ini” pun dianggap terlalu rancu. Saya paham, aturan ini dimaksudkan untuk menjaga relevansi, mengurangi bias, sekaligus membangun kredibilitas. Namun, apakah benar perlu sampai menyingkirkan segala bentuk ekspresi personal demi mengejar ‘objektivitas’? Objektivitas Bukan Berarti Tanpa Suara Dalam menuangkan gagasan, baik melalui lisan maupun tulisan, dunia akademik menuntut adanya asumsi dasar yang disebut sebagai objektivitas. Namun, sering kali kita keliru memahami objektivitas seolah-olah berarti menyingkirkan argumen pribadi penulis. Akibatnya, karya ilmiah menjadi sekadar repetisi teori orang lain tanpa menghadirkan orisinalitas. Jika demikian, kapan ruang bagi pelajar dan akademisi untuk mandiri dalam berpikir dan berani melahirkan ide-ide baru? Sejatinya, objektivitas dalam ilmu pengetahuan justru lahir dari subjektivitas yang teruji. Setiap ide, teori, atau hipotesis berangkat dari pemikiran subjektif individu atau kelompok, lalu memperoleh status objektif ketika argumen tersebut divalidasi melalui proses ilmiah. Kant (2008) dalam bukunya The Critique of Pure Reason bilang bahwa pengetahuan itu lahir dari pengalaman empiris yang bersifat subjektif dan struktur rasional dalam pikiran kita. Jadi, “objektivitas” bukan berarti bebas murni dari subjektifitas, melainkan hasil kerja sama antara pengalaman kita dengan kategori rasional yang sudah ada dalam diri manusia. Dengan kata lain, ada unsur subjektif yang di-“universalkan” oleh rasionalitas. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa menulis ilmiah yang terlalu kaku, seolah-olah tanpa ‘subjektivitas’, sebenarnya agak menyalahi hakikat ilmu itu sendiri. Karena sejatinya, setiap pengetahuan justru dimulai dari gagasan subjektif, baru kemudian ditempa lewat proses validasi. Kalau sistematika penulisan terlalu menekankan “objektif = tanpa suara penulis,” hasilnya sering monoton, miskin orisinalitas, dan kehilangan roh komunikasi. Padahal, kalau balik ke definisi KBBI, menulis itu “menuangkan gagasan melalui tulisan.” Artinya selalu akan ada suara pribadi yang hadir. Disuarakan Dulu, Dibuktikan Kemudian kita dididik untuk percaya bahwa sebuah gagasan sah hanya jika sudah dipublikasikan dan populer. Seolah-olah, pikiran pribadi tidak pernah cukup untuk berdiri sendiri. Jika setiap tulisan harus selalu menggandeng opini orang lain, lalu di mana ruang bagi orisinalitas? Bukankah pola ini justru menutup pintu lahirnya perspektif baru? Atau yang lebih parah, aturan ini menanamkan rasa takut: “Apakah gagasan saya benar? Atau ada yang lebih kredibel? Saya kan bukan siapa-siapa…” Inilah cacatnya sistem pendidikan kita. Hal yang dianggap “membantu” untuk melatih nalar kritis, justru berubah menjadi formalitas kaku yang membungkam keberanian berpikir.
Padahal, lihatlah sejarah. Newton bukan siapa-siapa ketika ia berandai-andai tentang gravitasi. Banyak rumus Einstein pun baru dibuktikan oleh orang lain bertahun-tahun kemudian. Mereka tidak menunggu validasi untuk berargumen. Lalu, mengapa sekarang kita begitu terobsesi agar setiap argumen harus divalidasi saat itu juga? Mengapa tidak kita biasakan dulu menyuarakan gagasan, lalu membuktikannya bersama-sama?
Ketika Akademia Terjebak Formalitas Receh Menurut saya, ‘gaya’ penulisan akademik tidak perlu dijaga seketat itu. Kalau alasannya sekadar formalitas, justru dangkal dan ironis. Masa dunia akademik yang menuntut argumen rasional, tapi soal teknis penulisan alasannya receh? Banyak penulis internasional yang membuktikan, riset serius bisa tampil cair tanpa kehilangan wibawanya. Thomas Erikson, misalnya, menyampaikan gagasan dan data dengan narasi yang terasa seperti percakapan hangat. Subjektivitas sesekali muncul, tetapi justru di situlah letak hidupnya tulisan, hal yang sayangnya, masih jarang diberi ruang dalam tradisi akademik kita. Gaya seperti itu juga bisa kita temui di buku yang berjudul The Good Life. Buku ini berangkat dari studi terpanjang tentang kebahagiaan, tapi alih-alih penuh dengan tabel dan angka, mereka justru mengisahkannya lewat potongan hidup nyata para partisipan. Rasanya bukan seperti membaca laporan riset, melainkan diajak menelusuri perjalanan manusia yang rapuh sekaligus kuat. Begitu juga dengan Mauro Guillén lewat 2030 (Twenty Thirty). Ia berhasil meramu data demografi, ekonomi, sampai teknologi menjadi cerita yang renyah dibaca, tanpa kehilangan kedalaman analisis.
Intinya, riset serius tetap bisa dikemas dengan gaya yang ramah. Dan kalau para penulis kelas dunia saja berani mengambil jalan itu, kenapa kita masih terjebak dengan bayangan “akademis” yang kaku? Dari sini, seharusnya kita berani keluar dari jebakan formalitas dangkal. Sebab, jika ilmu pengetahuan hanya diseragamkan dan berhenti pada publikasi jurnal yang dibatasi aturan formalitas tanpa memberi ruang kebebasan menulis dan mempublikasikan, maka pendidikan kita akan terus stagnan. Sebanyak apa pun riset dilakukan, jika tidak bisa menjangkau khalayak luas, ilmu itu kehilangan makna.
Selama mindset kita masih terpenjara oleh keraguan, pembatasan, serta obsesi menggandeng “otoritas Barat” demi kredibilitas, kapan kita bisa benar-benar merdeka dalam ilmu pengetahuan?
Penutup: Kebebasan yang Melahirkan Perubahan Bagi saya, merdeka tidak selalu berarti bebas dari penjajahan bangsa lain, melainkan juga bebas dari belenggu cara pandang sempit yang membatasi kreativitas. Dalam dunia akademik misalnya, ada anggapan bahwa tulisan harus selalu kaku, formal, dan sesuai pola tertentu. Padahal, dengan menulis jujur, sederhana, dan memberi warna pribadi dalam setiap argumen, kita tidak sekadar merdeka dari pakem lama. Akan tetapi, kita sedang membuka jalan agar gagasan dapat lebih mudah diterima, menggerakkan percakapan, dan pada akhirnya memberi dampak nyata bagi masyarakat.
Narasi: Akhsya Asyfa Azieda