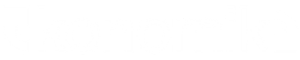Hari kemerdekaan merupakan nyanyian kebebasan yang tidak semua telinga mampu mendengarnya sebagai melodi merdeka. Tadeus, korban penjajahan geothermal di Flores mengatakan, “Jika kemerdekaan dipahami sebagai simbol pembebasan dari para penjajah, maka kami belum merdeka (Tim Floresa, 2024).” Begitu juga dengan Marsita, warga Rembang yang tergusur oleh PSN Rembang Eco City “Kami belum merdeka, mereka suka ria di Ibu Kota Nusantara (IKN), warga berjuang untuk kampung halaman (CNN Indonesia, 2024).” Nyatanya dibalik pembangunan megah Proyek Strategis Nasional (PSN) yang bertujuan untuk “Kesejahteraan Rakyat,” laporan tahunan agraria KPA 2023 menunjukkan adanya peningkatan konflik agraria dari tahun-tahun sebelumnya, tanah masyarakat direbut dan menyisakan dampak besar bagi kelompok marjinal, terutama perempuan. Perempuan tidak hanya kehilangan akses terhadap tanah yang dimilikinya, namun atas kerentanannya perempuan juga menghadapi berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi. Konflik agraria seringkali dipandang melalui sudut pandang masyarakat versus negara, sementara ketidakadilan yang dialami oleh perempuan di daerah konflik seringkali terlupakan. Tulisan ini akan membahas bagaimana perjuangan pencapaian “Kemerdekaan” perempuan di tanah yang terampas dengan studi kasus gerakan ekofeminisme yang diusung oleh Kartini Kendeng, serta menawarkan solusi untuk perjuangan perempuan lainnya dengan mengambil
pembelajaran dari gerakan yang terorganisir tersebut. Kartini Kendeng adalah kasus fenomenal bukan hanya tentang perampasan lahan, tetapi juga tentang perjuangan perempuan yang berhasil membawa isu regional ke tingkat nasional. Kasus ini menceritakan perlawanan perempuan Samin melalui Kelompok Perempuan Peduli Lingkungan (KPPL) serta perempuan pegunungan yang tergabung dalam Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) untuk menolak pendirian pabrik semen di atas sumber daya air masyarakat Kendeng, Pegunungan Kendeng, perlawanan ini kemudian akrab dengan sebutan Samin vs Semen.
Ibu Bumi telah menghidupi, Ibu Bumi telah disakiti, Ibu Bumi akan mencari keadilan,” ucap Sukinah anggota Kartini Kendeng (Pratiwi, 2023). Dalam perlawanan Samin vs Semen, masyarakat kendeng memaknai bumi sebagai Ibu. Ibu yang memberikan kehidupan melalui sumber dayanya sehingga masyarakat Kendeng dapat terus melakukan aktivitasnya, Ibu yang telah disakiti oleh para kapitalis industri semen yang hanya ingin mengeksploitasi sumber dayanya dan meraup keuntungan sebesar-besarnya, dan Ibu yang sampai sekarang masih mencari keadilan atas lahannya, perjuangan untuk keadilan lingkungan juga keadilan gender. Perspektif masyarakat Kendeng tersebut mencerminkan perspektif ekofeminisme yang pertama kali dijelaskan oleh Francoise d’Eaubonne dalam bukunya le féminisme ou la mort. Ekofeminisme merupakan isu kontemporer dalam gelombang ketiga feminisme yang membahas keterkaitan perempuan dengan lingkungan yang sama sama dieksploitasi oleh patriarki kapitalis (Mies & Shiva, 2014). Bumi dipandang sebagai Ibu, sama seperti perempuan pada umumnya. Ibu melahirkan dan memberi kehidupan, yang membuat kita hidup berkecukupan hingga saat ini. Ibu juga harus dirawat agar selalu sehat, sama seperti bumi yang harus dijaga agar tanahnya tetap subur dan terhindar dari kekeringan atau kerusakan. Bumi, seperti halnya perempuan, sering mengalami “Pemerkosaan” oleh proyek-proyek maskulinitas. Dalam kasus Semen vs Samin, perempuan yang terikat dengan pekerjaan domestik menjadi korban dari berkurangnya cadangan air pada Cekungan Air Tanah Watu Putih akibat dari penambangan. Seperti yang disampaikan Renaldi, “Soal lingkungan itu kan bukan cuma urusan bapak-bapak saja. Soal air itu kan lebih ke ibu-
ibu. Ibu-ibu di rumah kan bangun tidur yang dicari langsung air. Nyiapkan makanan, mencuci beras, memasak untuk keluarga. Jadi ibu-ibu ya merasa air itu bukan cuma kebutuhan bapak-bapak. Ibu-ibu itu merasa dialah yang berperan untuk menyiapkan kebutuhan keluarga (2017).” Tidak hanya itu, daerah resapan air pun berkurang akibat terjadinya pengerukan, sehingga petani Samin harus merasakan banjir baik pada tempat tinggalnya terkhusus pada lapangan pekerjaannya yakni lahan pertanian. Sebagai dampaknya, perempuan tidak hanya harus mencari air lebih jauh untuk menghidupi keluarganya, tetapi juga harus kehilangan pekerjaan akibat kegagalan panen yang dihadapinya. Tanah yang menjadi sumber kehidupan dirusak begitu saja. Namun, perempuan Samin tidak hanya tinggal diam. Untuk mencapai “Kemerdekaan” Samin membuat perlawanan yang terorganisir, sehingga mampu secara efektif menarik perhatian publik dan menekan pemerintah dengan bantuan dukungan dari masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun perempuan sering menjadi korban patriarki, mereka juga mampu melawan secara aktif dan strategis demi “Kemerdekaannya” Masyarakat kendeng secara mandiri berhasil mengorganisasi masyarakatnya dengan mendirikan Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK). JMPPK dengan ketua koordinatornya seorang perempuan merupakan sebuah organisasi yang menghimpun para petani di pegunungan Kendeng Utara dan Kartini Kendeng (Fitri & Akbar, 2017). Seiring berjalannya waktu, JMPPK kemudian memperluas jaringan dengan partisipasi yang berasal dari lembaga sosial, akademisi, aktivis NGO, hingga aktor individual dengan keahlian yang beragam (Syam, 2016). Peran sentral perempuan pada gerakan ini terlihat dalam beberapa perlawanan yang dilakukan, seperti pada Januari 2009, kartini kendeng melakukan aksi penghadangan mobil pabrik semen, pada Juni 2014 kartini kendeng mendirikan tenda tepat di depan pintu masuk pabrik semen, dan puncaknya pada April 2016, 9 kartini kendeng, yakni Sukinah, Karsupi, Sutini, Deni, Suraini, Ambarwati, Murtini, Giyem, dan Ngadinah menyemen kaki mereka di depan istana negara dan monas, tidak hanya sekali, pada Maret 2017 mereka kembali menyemen kaki mereka sebagai bentuk perlawanan terhadap kehadiran industri semen. Segala bentuk perlawanan yang dilakukan oleh Masyarakat kendeng berbentuk nirkekerasan. Walaupun tanpa kekerasan, Masyarakat Kendeng berhasil dalam hal publikasi, sehingga masyarakat awam menjadi sadar akan adanya isu tersebut dan secara tidak langsung hal ini mendorong masyarakat lain untuk turut menekan pemerintah, memperkuat posisi perjuangan Masyarakat Kendeng dalam menuntut keadilan dan mempertahankan hak-hak mereka. Perjuangan ini kemudian dikenal sebagai Kartini Kendeng. Layaknya Kartini yang memperjuangkan kemerdekaan pendidikan di Indonesia, perempuan-perempuan Kendeng pun berjuang untuk meraih kemerdekaan mereka sendiri: mempertahankan tanah, air, dan kehidupan
Di tengah riuh perayaan kemerdekaan ke-80 di Istana Merdeka, masih banyak masyarakat di daerah yang harus berjuang mempertahankan “Kemerdekaannya” dari perampasan tanah. Mereka tidak lagi dijajah bangsa asing, melainkan berhadapan dengan kapitalisme dan oligarki, bahkan kerap berseberangan dengan negara sendiri. Kisah Kartini Kendeng menjadi pengingat bahwa kemerdekaan sejati adalah kemerdekaan yang inklusif yang juga dirasakan oleh mereka yang berjuang menjaga tanah, air, dan kehidupan. Gerakan ini bukan hanya fenomenal, tetapi juga inspiratif bagi perjuangan perempuan di seluruh Indonesia untuk mencapai kemerdekaannya.
Narasi: Afina Putri Kusumadewi